
BAB 1
1.1 PENDAHULUAN
DNA merupakan bahan genetik
yang harus disampaikan kepada generasi berikutnya. Terdiri dari tiga komponen
utama, yaitu gugus fosfat, gula 5-karbon (deoksiribosa) dan basa nitrogen. DNA akan mengalami proses perbanyakan sebagai
salah satu tahapan sangat penting dalam proses pertumbuhan sel. Replikasi merupakan proses
pelipatgandaan DNA. Proses replikasi diawali dengan pembukaan untaian ganda DNA
pada titik-titik tertentu di sepanjang rantai DNA oleh enzim Helikase. Enzim
Helikase adalah enzim yang berfungsi membuka heliks ganda pada cabang replikasi
serta memisahkan kedua untai lama. Sintesis DNA berlangsung dengan orientasi 5’-Pà 3’-OH. Ada tiga jenis protein/enzim
yang berperan dalam sintesis DNA, yaitu DNA
Polimerase yang mengkatalisis
proses polimerasasi nukleotida menjadi untaian DNA. Menurut Yuwono (2008), pada
jasad prokariotik terdapat 3 macam DNA Polimerase, yaitu DNA Polimerase I, DNA
Polimerase II, dan DNA Polimerase III. Pada jasad eukariotik terdapat 5 macam
DNA Polimerase, yaitu DNA Polimerase α, DNA Polimerase β, DNA Polimerase γ, DNA
Polimerase δ dan DNA Polimerase ε. Sedangkan DNA Ligase, yaitu suatu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA
dimana ligase mengkatalisis penyatuan dua molekul yang berpasangan dengan
pemecahan ikatan pirofosfat dalam ATP atau trifosfat serupa dan DNA Primase bertugas mengkatalisis sintesis primer untuk
memulai replikasi DNA.
Kesalahan dalam menggabungkan
basa dapat saja terjadi. DNA Polimerase I dan III mengandung aktivitas
eksonuklease 3’-5’ yang berfungsi untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan
tersebut. Nukleotida yang tergabung secara tidak tepat dilepaskan sebelum
rantainya tumbuh lebih panjang. DNA juga dapat mengalami kerusakan yang
disebabkan oleh beberapa zat termasuk radiasi ultraviolet, radiasi pengionan
dan berbagai macam bahan kimia. Kerusakan molekul seperti itu dapat menyebabkan
kerusakan bahkan kematian pada makhluk hidup
DNA
sebagai materi genetic yang selalu mengalami berbagai reaksi kimia dan selalu
melakukan kopi DNA. Perubahan struktur DNA ini disebut mutasi DNA yang dapat
terjadi pada saat proses replikasi DNA. Untuk menstabilkan hal tersebut maka
DNA memiliki kemampuan untuk memperbaiki (repair) kesalahan yang terjadi pada
dirinya sendiri. Jika mutasi DNA yang terjadi cukup banyak dan DNA tidak sempat
untuk memperbaiki (repair) dirinya sendiri maka akan terjadi kelainan ekspresi
genetic bahkan menyebabkan terjadinya penyakit genetik. Konsumsi makanan yang
bergizi serta istirahat yang cukup memungkinkan tubuh untuk dapat melakukan
repair DNA.
DNA
repair merupakan suatu mekanisme perbaikan DNA yang mengalami kerusakan /
kesalahan yang diakibatkan oleh proses metabolisme yang tidak normal, radiasi
dengan sinar UV, radiasi ion, radiasi dengan bahan kimia, atau karena adanya
kesalahan dalam replikasi DNA. Mekanisme perbaikan yang terdapat ditingkat
selular secara garis besar disesuaikan dengan jenis kerusakan yang tentu saja
terkait erat dengan jenis factor penyebabnya. Sel-sel menggunakan
mekanisme-mekanisme perbaikan DNA untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan pada
sekuens basa molekul DNA. Kesalahan dapat terjadi saat aktivitas selular normal,
ataupun dinduksi. DNA merupakan sasaran untuk berbagai kerusakan: baik
eksternal agent maupun secara spontan.
BAB II
2.1 Sejarah
Penemuan DNA
Secara garis besar, peran DNA di dalam sebuah sel adalah sebagai materi
genetik; artinya, DNA menyimpan cetak biru bagi
segala aktivitas sel. Ini berlaku umum bagi setiap organisme. Di antara
perkecualian yang menonjol adalah beberapa jenis virus (dan virus tidak
termasuk organisme) seperti HIV (Human Immunodeficiency
Virus).
DNA pertama kali berhasil dimurnikan pada tahun 1868 oleh ilmuwan Swiss Friedrich Miescher di Tubingen, Jerman, yang menamainya nuclein berdasarkan lokasinya di dalam inti
sel. Namun demikian, penelitian terhadap peranan DNA di dalam sel baru dimulai
pada awal abad 20, bersamaan dengan ditemukannya postulat genetika Mendel. DNA dan protein dianggap dua molekul yang paling memungkinkan sebagai pembawa sifat
genetis berdasarkan teori tersebut.
Dua eksperimen pada dekade 40-an membuktikan fungsi DNA sebagai materi
genetik. Dalam penelitian oleh Avery dan rekan-rekannya, ekstrak dari sel bakteri yang satu gagal men-transform sel bakteri lainnya kecuali jika DNA dalam ekstrak dibiarkan utuh. Eksperimen yang dilakukan Hershey dan Chase membuktikan hal yang sama dengan menggunakan pencari jejak radioaktif (bahasa Inggris: radioactive tracers).
Misteri yang belum terpecahkan ketika itu adalah: bagaimanakah struktur
DNA sehingga ia mampu bertugas sebagai materi genetik? Persoalan ini dijawab
oleh Francis Crick dan koleganya James Watson berdasarkan hasil difraksi sinar X pada DNA oleh Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin.
Pada tahun 1953, James Watson dan Francis Crick mendefinisikan DNA
sebagai polimer yang terdiri dari 4 basa dari asam nukleat, dua dari kelompok purina:adenina dan guanina;
dan dua lainnya dari kelompok pirimidina:sitosina dan timina. Keempat nukleobasa tersebut terhubung dengan glukosa
fosfat.
Maurice Wilkins dan Rosalind Franklin menemukan bahwa molekul DNA
berbentuk heliks yang berputar setiap 3,4 nm, sedangkan jarak antar molekul nukleobasa
adalah 0,34 nm, hingga dapat ditentukan bahwa terdapat 10 molekul nukleobasa
pada setiap putaran DNA. Setelah diketahui bahwa diameter heliks DNA sekitar 2 nm, baru diketahui bahwa DNA terdiri bukan dari 1
rantai, melainkan 2 rantai heliks.
Crick, Watson, dan Wilkins mendapatkan hadiah Nobel Kedokteran pada 1962 atas penemuan ini. Franklin, karena sudah wafat pada waktu
itu, tidak dapat dianugerahi hadiah ini.
Konfirmasi akhir mekanisme replikasi DNA dilakukan lewat percobaan
Meselson-Stahl yang dilakukan tahun 1958.
2.2 Mengungkap Rahasia Reparasi DNA
Thomas
Carell dan Eva Bürckstümmer di Ludwig Maximillan University of Munich, Jerman,
telah membuat rantai-rantai DNA pendek yang mengandung lesi (cacat/luka).
Carell menjelaskan bahwa ini adalah kunci untuk memahami reparasi DNA.
"Sejauh ini, semua penelitian yang dilakukan terhadap proses yang
membingungkan ini dihambat oleh kurangnya DNA yang mengandung lesi-lesi
ini," paparnya.
Lesi-lesi yang terdapat pada DNA ini analog
dengan lesi yang timbul apabila sinar UV mengenai DNA yang tersimpan dalam
spora seperti spora bakteri Bacillus. Di alam, spora-spora ini bisa menjadi
tidak aktif (dorman) selama bertahun-tahun, dengan menyimpan DNA, tetapi
kemudian hidup kembali, papar Carell. Bagaimana spora menyimpan DNA dan
bagaimana reparasi lesi terjadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang ingin dijawab
oleh dua peneliti Jerman ini.
Carell dan Bürckstümmer
membuat rantai-rantai DNA mereka dengan mensintesis dua isomer dari sebuah
analog lesi dinukleotida dan memasukkannya ke dalam DNA. Mereka menemukan bahwa
salah satu DNA lebih stabil dibanding yang lainnya, sehingga menandakan bahwa
lesi alami bisa memiliki struktur yang mirip dengan analognya dalam DNA yang
lebih stabil. Carell menyebutkan bahwa analog-analog lesi yang serupa adalah
substrat untuk enzim reparasi DNA spora sehingga rantai-rantai DNA yang baru
bisa membantu dalam meneliti lebih lanjut tentang mekanisme enzim ini.
Glen Burley, seorang ahli
di bidang nanoteknologi DNA di Universitas Leicester, Inggris, mengatakan bahwa
penelitian ini menarik karena menemukan sebuah metode untuk meneliti bagaimana
spora bakteri mereparasi DNA yang rusak. "Mekanisme yang terlibat perlu
segera diketahui karena proses kerusakan DNA pada spora berbeda dengan yang
terjadi pada mamalia," kata dia. "Metode-metode ini kemungkinan akan
membuka pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana spora bisa bertahan hidup
selama periode waktu yang lama dan pada kondisi-kondisi yang tidak cocok –
misalnya pada sumber mata air panas atau dibawah keterpaparan sinar UV."
Carell menjelaskan bahwa
walaupun proses reparasi pada spora berbeda, tetapi fenomena pengenalan lesi
oleh enzim bersifat umum. "Enzim-enzim seperti ini juga bekerja dalam
sel-sel kita," kata dia, "sehingga pemahaman yang lebih mendalam
tentang kelompok enzim yang membingungkan ini diperlukan." Carell
menambahkan bahwa dia tertarik dalam mempelajari lebih banyak tentang
kegagalan-kegagalan proses reparasi. "Kegagalan-kegagalan reparasi DNA ini
bertanggungjawab untuk terjadinya mutasi yang selanjutnya mengarah pada situasi
seluler berbahaya yang bisa menghasilkan kanker," ungkapnya.
DAFTAR
PUSTAKA
http://id.shvoong.com/medicine-and-health/genetics/2077854-dna-repair perbaikan-dna/
http://kamriantiramli.wordpress.com/2011/04/26/
http://www.rsc.org/chemistryworld/
Amstrong, F, B,.2001. Buku ajar biokimia
edisi 3. Alih bahasa dr. RF. Maulany, MSc. Penerbit EGC: Jakarta.
Anonim, http://en.wikipedia.org/wiki/DNA_repair
Campbell, N, A,. 2002. Biologi. Alih bahasa Rahayu lestari (et.al). Erlangga: Jakarta
Murray, R.K., [et.al]. 2003. Biokimia Harper Edisi 25.
Jakarta : EGC.
Soemiaty, A, M,. 1989. Pedoman Kuliah Biologi
Sel, PAU-Bioteknologi, Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta
Yuwono, T., 2008.
Biologi Molekuler. Erlangga: Jakarta
(www.wikipedia.org/wiki/DNA_repair).


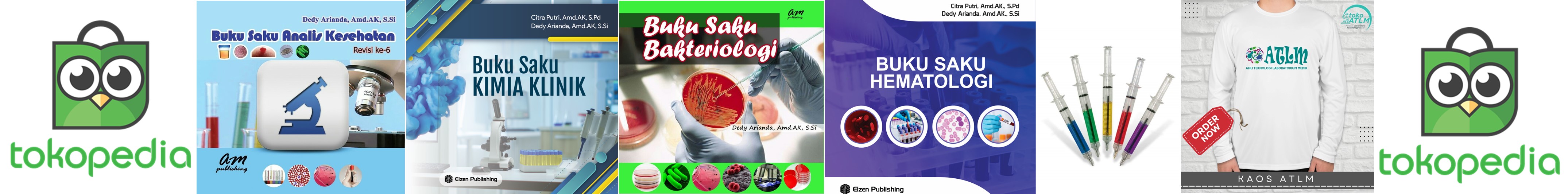
Posting Komentar